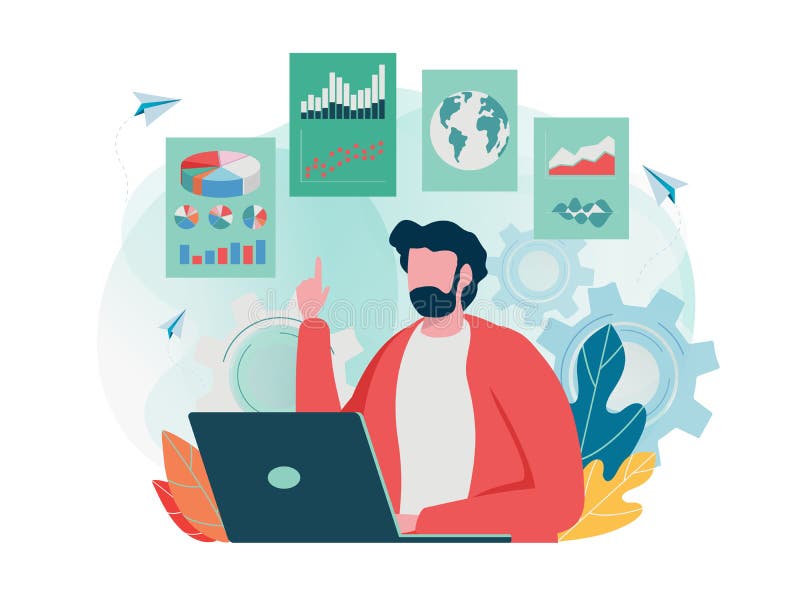Hari
ini, kita tahu bahwa setiap hari kita selalu melihat beragam cerita. Sajian
demi sajian cerita-ceritanya hampir terus menyesaki ruang pandang dan ruang
dengar. Lalu kita menikmati dan terhanyut dalam setiap alurnya atau kadang muak
dengan semua cerita-cerita yang terus disuguhkan. Seperti ketika kita melihat
teater, saat semua pemain memperkenalkan diri, kita menyoraki; gembira atau
menghina. Saat pemain mengundurkan diri
menyudahi lakonnya, ada yang memuji bahkan memaki atas ketidakpuasan saat
melihatnya.
Di
negeri ini hal di atas seperti pengejawantahan dari lakon-lakon teater saja.
Semakin banyak lakon memainkan perannya, maka semakin banyak komentar-komentar
penonton bertebaran dalam ruang itu. Saking banyaknya komentar, kita seperti
berada di pasar burung. Setiap sudut pasar yang kita datangi, selalu ada
kicauan. Semakin banyak burung yang dipamerkan, kicauan burung bukan tambah
mengurang tapi tambah ramai.
Perpolitikan
di negeri ini tak jauh beda dengan ‘pasar burung’. Burung dengan kicauannya
yang cantik, ia akan menjadi burung yang mahal dan banyak digemari ̶ meski kita tahu, burung dengan kiacauan
terbaiknya akan berkicau bila istana sangkarnya dipenuhi pakan bergizi yang
baik untuk tubuhnya. Ada kemauan di balik kicauan. Namun, bila burung itu
memiliki kicauan yang tidak menarik perhatian orang, jelek, ia tak begitu
berharga bahkan dilirikpun tidak. Anda pasti tau, bahwa yang membedakan
diantara keduanya terletak pada ‘nilai’ yang terdapat dalam burung-burung itu.
Hari
ini kita banyak melihat karakter bangsa di negeri ini seperti burung dengan
kicauannya yang indah. Kita tahu kicauan itu sangat baik bagi pendengaran
setiap kali kita mendengarnya. Namun, dan ini yang menjadi persoalan, tidak
semua kicauan mengandung nilai, bila hal itu tidak didasarkan pada kebaikan
yang dikicaukan. Analoginya, kita juga tahu, di negeri ini banyak orang
berperan seperti pahlawan super hero dengan lantang menyuarakan tentang hal-hal
yang berkaitan dengan negara, mengangkat martabat bangsa dan negara, revolusi
mental, bersama melawan KKN, dan lain-lain yang bernuansa seolah menyelamatkan
negara. Padahal apa yang disampaikan sebetulnya berorientasi pada tujuan-tujuan
tertentu: mengincar kursi kekuasaan, menyelamatkan diri dari sesuatu yang salah
diperbuat dan atau meraup keuntungan sebagai ladang mata pencaharian.
Pada masa kepemimpinan Muawiyah, seorang komandan pasukan bernama Al-Hurr diutus untuk mencegah Sayyidina Husain bin Ali, cucu Rasulullah SAW di sebuah padang pasir di negeri seribu satu malam, Irak. Dia sadar benar bahwa Husain sedang memperjuangkan kebenaran: membela rakyat yang tertindas. Suatu perjuangan yang sebenarnya sedang ia perjuangkan juga. Namun dia terikat oleh sumpah prajuritnya. Ketika jendral Sa’ad mengutus untuk membunuhnya, dia pun membelot membela Sayyidina Husain bin Ali. Hal ini Al-Hurr lakukan demi membela keyakinannya pada kebenaran. Cerita ini menjadi contoh yang baik dari peran orang yang baik. Al-Hurr bukan sekedar sosok pemimpin yang baik dengan segenap keberanian yang dimilikinya. Namun, di balik semua itu, ia memilik ‘nilai’ positif dalam kepemimpinannya: kebaikan bernilai baik.
Baca juga PERADABAN QABIL
Di
negeri ini sebetulnya tidak membutuhkan sosok pemimpin yang hanya bermodal
pemberani. Di sisi lain, kita perlu memiliki pemimpin yang baik dan memiliki
tujuan yang baik pula. Bukan hanya itu, ia bisa menciptakan cerita yang baik.
Tentunya, ia juga mengerti bagaimana kebaikan itu terus berjalan pada arah yang
baik. Sebab, tujuan yang baik bukan berarti menjadikan perbuatan itu baik. Terkadang
kebaikan bila tidak melintasi pada jalannya yang baik, malah menimbulkan
sesuatu yang tidak baik. Buruk.
Selanjutnya,
kita sebagai bangsa hanya perlu menolak secara bersama-sama terhadap karakter
pemimpin yang tidak berdasarkan ‘nilai’ dalam kepemimpinannya. Tentunya dengan
demikian, ketentraman di negeri ini akan berjalan langsung tanpa menyalahkan,
membenarkan, atau abai tapi tetap dalam bendera Bhineka Tunggal Ika. Dengan demikian bangsa kita tidak menjadi
bangsa kasihan. Meminjam metafor Kahlil Gibran, bangsa kita ini jatuh menjadi
bangsa kasihan. Yakni, bangsa yang negarawannya serigala, filosofnya gentong
nasi, dan senimannya tukang tambal dan tukang tiru. Bangsa yang menyambut
penguasa barunya dengan terompet kehormatan, namun melepasnya dengan cacian,
hanya untuk menyambut penguasa baru lain dengan terompet lagi. Bangsa yang orang sucinya dungu menghitung
tahun-tahun berlalu dan orang kuatnya masih dalam gendongan. Bangsa yang
terpecah-pecah dan masing-masing pecahan menganggap dirinya bangsa.
Muhammad Faisal Ali